STARJOGJA.COM, Magelang – Hari Jumat pekan lalu jadi bagian ilmu yang tidak terlupakan. Pagi hari kabar duka datang teman jurnalis Solo. Ayahanda teman penulis saya ini meninggal seusai dzikir shubuh. Informasi itu lantas sampai ke saya melalui teman penulis lain bernama Edhi yang kebetulan satu daerah dengan teman saya.
Kaget dan jelas ikut bersedih dengan kabar itu. Reaksi normal jika teman mendapatkan yang bagi kita disebut halangan. Melalui aplikasi pesan singkat kami pun janjian ke rumah duka di Watu Congol, Muntilan, Magelang Jawa Tengah. Edhi pun meminta agar saya melewati jalur Kalibawang agar cepat sampai. Walaupun sebelum idenya muncul saya sudah memiliki niat melintas jalan itu.
Bagi saya jalan baru itu seolah menantang untuk dilalui. Karena belum tahunya saya dengan jalan baru tentu saya akan memiliki pengalaman yang baru. Jalan, udara, jalur, pohon, air sungai yang dilewati hingga pemadangan alam jadi teman perjalanan ke rumah duka.
Baca Juga : Cerita di Balik Nama Kampung di Jogja
Sampai mendekati lokasi rumah duka, waktu sudah menunjukkan sholat Jumat saya pun teringat ini Hari Jumat. Bathin saya ahh karena ini masalah kemanusiaan, pertemanan, dan mahluk hidup maka berencana tidak sholat Jumat. Beberapa masjid sudah menggelar sholat Jumat ketika berkendara. Sudahlah sepertinya sholat Jumat pun tidak dilaksanakan.
Tapi, saya kemudian berbicara dengan Tuhan kalo misalnya ada masjid yang masih “menyediakan” sholat Jumat maka saya akan berhenti. Itu pun harapannya sholatnya cepat dan ketika ke lokasi rumah duka saya tidak ketinggalan prosesi acara pemakaman.
Keinginan ini sepertinya juga membuat saya merasa bersalah. Karena ketika tiba di rumah duka yang sebelumnya tidak tahu lokasi, karena awalnya janjian dengan Edhi. Tiba-tiba ketika ketemu di persimpangan melihat rumah dengan tratak, kursi berjejer, karangan bunga dengan nama mirip teman saya. Benar ternyata, itu rumah duka yang saya cari.
Belum banyak orang karena kebanyakan masih melaksanakan sholat Jumat termasuk teman saya. Hmnn karena ingin cepat datang, sepertinya saya yang pertama yang datang ke rumah duka dibandingkan teman jurnalis maupun penulis lainnya. Jika melihat lagi, sejak saya datang hingga pemakaman itu memiliki jeda waktu 2-3 jam. Pada akhirnya saya malu dengan keinginan saya yang “dikabulkan” Tuhan.
Setelah sholat Jumat selesai, akhirnya saya ketemu dengan teman saya. Saya mencoba dia tegar namun tidak ada raut sedih dari teman saya ini. Begitu juga kakaknya. Senyum terlihat ketika menerima tamu dari warga sekitar ataupun teman-temanya. Tidak terlihat wajah sedih dari pihak keluarga. Ibunda teman saya lebih banyak di dalam rumah baru terlihat ketika malam hari saat saya akan pamit pulang.
Tidak lama Edhi teman saya sampai juga di rumah duka. Sedikit bercengkrama kami pun bertiga larut dalam perbincangan. Termasuk kondisi ayahanda sebelum meninggal. karena teman saya harus menerima tamu-tamu lain maka saya dan Edhi mencari tempat sendiri.
Lalu, saya bertanya ke Edhi, “Mas disini semuanya terlihat enak ya? Tidak ada sedih, merasa ditinggalkan atau lainnya.”
“Kalo disini memang gitu. Meninggal itu disini biasa saja. Tidak ada rasa sedih. Sedih itu tidak diperlihatkan,” jawabnya.
Makanya yang keluar adalah senyum, dan tidak sedih. Filosofi itu bagi saya sangat hebat karena ini tentu berbeda dengan pandangan orang kota. Kejadian meninggal diartikan kesedihan, perpisahan, tangis dll. Hari itu, Watu Congol membuat saya tersadar memang seperti itu seharusnya.
Prosesi pemakaman di Hari Jumat pun dimulai dengan acara-acara seperti pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada pemandangan yang unik saat pembacaan ayat suci oleh qori. Saat itu cuaca sudah mulai rintik hujan. Padahal Edhi mengaku sebelum masuk wilayah Muntilan, Magelang dilanda hujan deras. Sampai ia tidak dapat melihat jalanan dari Semarang.
Seorang yang menurut saya agak stress dengan jas merah bercelana pendek berjalan menuju qori. Sesampai didepan qori ini “Wes ndang cepet mocone selak udan barang kok, kesuwen,” katanya dengan nada marah.
Memang benar sih, kalo cuaca sedang rintik hujan. Namun mungkin orang tidak mau menegur karena membaca ayat suci saja kita tidak berani menghalangi. Kemudian, karena ini acara layatan tentu segan untuk menegur juga. Sampai orang stress itu datang maka saya pun lega akhirnya.
“Disini itu orang kenthir malah diajeni, coba liat nanti dia pasti dikasih sesuatu. Orang kenthir itu malah dianggap biasa saja. Bahkan mungkin dianggap memiliki kelebihan. Maka disini orang kenthir ini ya kayak orang biasa saja,” kata Edhi.
Benar juga, tidaklama laki-laki kenthir berjas merah itu dikasih orang sekitar sesuatu. Sepertinya sih uang. selama acara layatan juga tidak ada penutupan jalan. Karena warga sekitar sudah menganggap meninggal ini tidak membuat oranglain kesusahan. Itu juga yang diucapkan temen saya Edhi.
Setelah selesai, Edhi bergegas mendekat keranda. Ia pun memilih mengangkat keranda bersama warga sekitar di bagian paling depan. Tidak ada aturan khusus siapa yang harus menggotong keranda itu hingga liang lahat. Semua orang pun boleh, termasuk teman saya itu.
Sampai di liang lahat, gerimis di hari Jumat itu sudah terlihat lagi. Ketika jenazah sudah dikebumikan ustad atau kyai setempat membacakan doa. Teman saya Edhi juga ikut berdoa. Mengamini dan ikut membaca Alfatihah. Sejujurnya saya juga tidak tahu apa agama teman saya ini. Saya pun tidak seolah merasa tidak sopan untuk bertanya. Karena, agama itu urusan dirinya dengan Tuhan. Sepakat dengan anggapan teman saya, yang penting itu adalah berbuat baik dengan orang dan tidak mencelakai orang lain itu sudah cukup. Karena selama ini ia tidak pernah mencelakaiku bahkan seringnya ngasih duit saya ya bagi saya ia menganut agamanya dengan baik.
Anehnya setelah prosesi pemakaman selesai, hujan deras turun. Ini agak aneh juga seolah alam ikut mendukung dengan prosesi pemakaman. Bahkan kita terjebak di pemakamanitu bersama teman saya. Di kesempatan itu saya pun memiliki banyak waktu untuk bercerita tentang banyak hal termasuk kyai di Watu Congol.
Bagaimana Kyai disana sangat kental dengan ilmunya yang tinggi. Bahkan Gusdur, Gus Miek itu terakhirnya belajar di pondok Watu Congol. Satu hal yan gsaya rasakan dan alami berada sehari disini kedekatan dengan alam dan Tuhan begitu terasa.
Jadi, kabar duka hari itu menjadi intropeksi saya hidup dengan alam, manusia dan Tuhan. Apapun kejadiannya jika kita kembalikan ke Tuhan pasti semuanya menjadi ilmu dan hikmah sendiri. Itu pun jika kita ingin dan mau untuk mendalaminya. Hari Jumat itu menjadi penanda bagi saya untuk terus menyelami kehidupan.


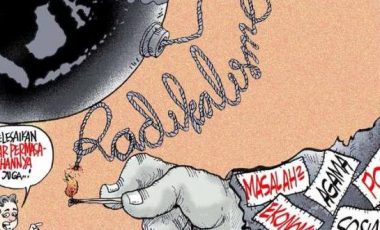




Comments